Saat Tet tahun ini, saya pulang kampung untuk membakar dupa bagi orang tua saya. Anehnya, setelah puluhan tahun jauh dari rumah, sebelum mereka meninggal, mereka masih memiliki hasrat yang membara untuk dimakamkan di kampung halaman mereka. Namun, setelah bertahun-tahun, anak dan cucu mereka akhirnya dapat mewujudkan keinginan itu.
Aku bisa merasakan kembali suasana Tet di kampung halamanku dulu. Malam masih dipenuhi aroma bunga jeruk bali, bunga blackberry, dan bunga-bunga lainnya... lembut dan murni, samar-samar membuatku menemukan perasaan asing namun familiar di hatiku. Di halaman belakang, suara gemerisik daun pisang yang bergesekan, berbisik lembut seolah mengingatkanku pada hal-hal yang sangat kecil namun luar biasa penting, meskipun terkadang terabaikan dan terlupakan, tetapi setiap kali kutemui, aku tak kuasa menahan diri untuk tak tersentuh.
Kisah-kisah di antara aroma bunga di tengah pekatnya malam selalu merupakan kisah tentang kerabat, tentang leluhur kita di masa lalu, meskipun hidup sangat kekurangan, semua orang miskin, tetapi mengapa mereka begitu baik, peduli, dan penuh kasih, bahkan rela berkorban makanan dan pakaian? Sampai-sampai kita selalu berpikir bahwa generasi kita tidak dapat memperlakukan satu sama lain sebaik generasi sebelumnya. Ada satu hal yang benar-benar membingungkan saya, ketika kehidupan semakin makmur, orang-orang seringkali mudah terpecah belah, memiliki banyak kecemburuan dan perhitungan untung rugi bahkan di antara sesama saudara...

Jalan pedesaan - Foto: Giac Ngo Online
Bagi banyak orang yang jauh dari rumah dan tidak dapat pulang, Tet selalu menjadi duka mendalam bagi tanah air mereka. Tet tetap menjadi kesempatan, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi kerabat. Bertemu dan berkunjung juga merupakan reuni yang membahagiakan.
Saya sungguh tersentuh ketika melihat dua vas berisi bunga panjang umur segar di batu nisan orang tua saya, dan sebelumnya ada buah-buahan dan sekotak kue di batu nisan di akhir tahun, yang ditinggalkan sejak hari-hari pertama tahun itu; bahkan saudara-saudara di pedesaan pun tidak tahu siapa pemiliknya, karena telah melakukan hal yang begitu diam namun bermakna bagi saya. Saya tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi jauh di lubuk hati saya merasa bangga, bagaimana orang tua saya hidup ketika mereka masih hidup sehingga kerabat masih menyimpan perasaan yang begitu berharga.
Dalam perjalanan membakar dupa, melewati parit-parit, di musim semi, rumput kembali menghijau, sapi-sapi perlahan merumput di parit-parit. Hari-hari pertama tahun baru di pedesaan, gerimis masih terasa, hujan musim semi tak cukup membasahi bahu orang-orang, tetapi cuaca begitu dingin sehingga saya harus mengenakan dua baju hangat.
Di ladang-ladang kosong yang berangin, hawa dingin semakin terasa. Tiba-tiba, kulihat beberapa anak menggembalakan sapi-sapi dengan pakaian tipis, duduk menggigil di jalan. Beberapa dari mereka bersandar di dinding makam untuk menghindari dingin. Aku tak kuasa menahan rasa sedih, bayangan-bayangan puluhan tahun lalu tiba-tiba muncul.
Dalam hidup, kita sering terbiasa melihat ke atas, gambaran itu diam-diam mengingatkan saya bahwa ada kalanya saya perlu melihat ke bawah. Selama puluhan tahun, di hari raya Tet, masih ada anak-anak menggembalakan sapi, menggigil kedinginan, penuh simpati.
Tiba-tiba saya teringat syair-syair penyair Trieu Phong, yang menghabiskan masa kecilnya menggembalakan sapi di Ru Tram, di tepi utara Sungai Thach Han. Ia telah tiada, tetapi ia meninggalkan puisi-puisi tentang tanah airnya yang cukup untuk membangkitkan rasa cinta yang mendalam kepada orang tua dan tanah airnya:
“... Anak gembala sapi mengikuti ibunya melalui banyak perjalanan yang sulit/ Ayahnya terkejut/ Anak gembala sapi itu bisa menulis puisi/... Jika dia tidak menggembalakan sapi di masa kecilnya/ Bagaimana dia akan menyeberangi lereng Con Kho menuju hutan Tram/ Bagaimana dia akan tahu cara memetik kayu sim yang diikat dengan garpu senja berwarna hijau tua/ Dan bagaimana dia akan melihat warna ungu yang tersembunyi di semak berduri...”.
Masa kecil setiap orang yang menggembalakan sapi juga terkait erat dengan suatu tempat, cinta dan kesulitan yang berbeda, terutama terkait dengan sekuntum bunga, pohon endemik pedesaan yang disaksikan penyair Trieu Phong dari masa kecilnya yang malang sebagai penggembala sapi. Dan dari tempat itu, dalam situasi itu, puisi lepas landas, melayang bersama keyakinan akan kehidupan: "...Aku bernyanyi bersama bunga-bunga sepanjang pencarian / Oh bunga-bunga sore / Tetaplah hijau bagai cinta yang hilang...". Dua baris penutupnya sedih tetapi sama sekali tidak tragis, membacanya membuat kita merasakan kesedihan yang mendalam.
Ayat-ayat itu menjadi penghiburan hangat bagi saya di tengah pikiran dan belas kasih saya.
Begitu pula dengan secangkir teh di pagi hari, di samping pohon aprikot, kuningnya waktu namun tak pudar, namun murni bagai dedaunan, bunga, dan rerumputan, tanpa rasa khawatir, hanya tahu bagaimana menyampaikan perasaan masing-masing. Suara orang-orang saling menyapa dan mengucapkan Selamat Tahun Baru di luar gerbang terngiang-ngiang, membuatku ikut merasa bahagia. Aku sangat merindukan Tet di kampung halamanku. Aku merindukan mereka yang merantau di negeri asing dan tak pernah kembali merayakan Tet di desa asal mereka.
Ho Si Binh
Sumber

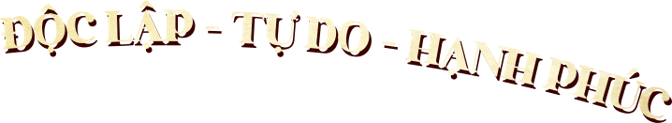







![[E-Magazine]: Tempat itu begitu bergairah hingga membuat jantungmu berdebar kencang](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/22/ac7c83ddf6dc43a49a177f8f8bc2262d)


























































































Komentar (0)