1. Pernahkah kau bertanya-tanya dari mana datangnya keteguhan? Bagiku, keteguhan itu ditemukan di pundak ayahku, bagaikan akar pohon tua yang menancap kuat di tanah, berdiri tegak melindungiku melewati badai. Ayahku, pria yang tak banyak bicara dengan tangan kasar, namun cukup kuat untuk menopangku seumur hidupku. Aku tumbuh dewasa, tetapi mata ayahku dipenuhi pikiran, bagaikan batuan sedimen berusia ribuan tahun, menceritakan banyak kekhawatiran yang tak pernah ia keluhkan. Dalam ingatan itu, aku melihat diriku sebagai perahu kecil, terombang-ambing di lautan, dan mercusuar yang menuntunku adalah bayangan ayahku, kokoh dan tak pernah padam. Aku ingat, di senja hari, sinar terakhir hari itu masih menyinari punggung ayahku yang membungkuk saat ia duduk di beranda, dengan tekun memperbaiki sepeda yang baru saja kurusak karena terlalu asyik bermain. Noda-noda minyak itu tak hanya menempel di tangan ayahku, tetapi juga terpatri kuat di benakku setiap kali aku melakukan kesalahan.
Aku takkan pernah melupakan pagi-pagi buta itu, saat aku berumur 10 tahun, mengikuti ayahku ke sawah untuk menimba air melawan kekeringan. Embun pagi bertebaran di sawah, angin sejuk berembus di sela-sela batang padi kering, membawa aroma tanah yang baru dipecah dan aroma aluvium yang samar. Aku meronta-ronta memegang ember, tanganku masih lemas, tak mampu menariknya. Kemudian ember itu terlepas dari tanganku dan jatuh ke dalam parit. Aku tertegun, kekecewaan menyelimutiku saat melihat ember itu tenggelam. Mendengar suara itu, ayahku bergegas menghampiri. Bayangannya jatuh panjang di tanah, begitu cepat hingga aku merasa seperti embusan angin yang lewat. Ayahku berlutut dan mencelupkan tangannya ke dalam air dingin, mencari ember itu. Tangannya penuh kapalan, tetapi saat itu aku merasakannya luar biasa kuat. Ayahku mendekat ke telingaku, berbicara lembut, suaranya dalam dan mantap, lebih mantap daripada guntur: "Tenanglah, Nak. Semuanya akan baik-baik saja." Ayahku mengambil ember itu dan meletakkannya di tanganku, bersinar dengan keyakinan yang tak terbatas. Ia tidak memarahiku, hanya diam menggenggam tanganku, menuntunku menyusuri setiap cipratan air. Pagi itu, perjalanan dari ladang ke rumah terasa lebih pendek.
2. Aku masih melihat bayangan ayahku duduk termenung dengan secangkir teh pagi, matanya menatap jauh ke halaman yang kosong. Garis-garis di dahinya adalah bukti dari banyak malam tanpa tidur, dari saat-saat ia terjaga mengkhawatirkan masa depan kami. Setiap kali aku jatuh, ia tidak terburu-buru membantuku, tetapi membiarkanku berdiri sendiri, matanya mengikutiku, bersinar dengan keyakinan bahwa aku bisa melakukannya. Kemudian ayahku jatuh sakit, saat itu sore di awal November, gerimis terus-menerus diikuti oleh angin utara yang dingin. Ia baru saja kembali dari pabrik, mantel pudarnya tidak cukup hangat, seluruh tubuhnya gemetar. Malam itu, ia batuk hebat, suaranya serak, matanya lelah tetapi ia masih berusaha tetap tenang. Ibu saya pergi, saudara-saudara saya dan saya terlalu muda untuk sepenuhnya memahami kelelahan ayah saya. Saya duduk di samping tempat tidur, tangan kecil saya menyentuh lengan ayah saya, merasakan urat-uratnya menggembung.
Aku sangat khawatir, tetapi tak berani menangis. Tiba-tiba, ayahku membuka matanya. Matanya cekung dan lelah, tetapi ia tetap berusaha menatapku. Ia mengulurkan tangan, gemetar, dan membelai rambutku dengan lembut. Senyum tipis tersungging di bibirnya, sekuat lilin yang tertiup angin. "Jangan khawatir, Nak. Aku baik-baik saja."... Suaranya lemah dan parau, tetapi itu mengusir rasa takut yang menyelimutiku. Keesokan paginya, meskipun masih lelah, ayahku mencoba bangun. Aku melihatnya diam-diam pergi ke dapur untuk memasak sepanci bubur jahe hangat, lalu tertatih-tatih menyiapkan bahan-bahan untuk berangkat kerja. Kakinya masih gemetar, tetapi setiap langkahnya mantap. Ia tak ingin kami melihatnya lemah, tak ingin pekerjaannya terabaikan. Saat itu, aku mengerti bahwa kasih sayang seorang ayah bukan hanya sumber yang lembut, tetapi juga batu karang yang kokoh, abadi, teguh, dan tak bersuara, bahkan ketika tubuhnya bergulat melawan penyakit.
3. Kini setelah dewasa dan menjalani hidup sendiri, aku semakin mengerti. Setiap keputusan yang kuambil, setiap kesuksesan yang kuraih, selalu dibayangi ayah, diam-diam mendukung dan menunjukkan jalan. Ayah bukanlah cahaya terang yang menerangi jalan, ia adalah gunung kokoh dan teguh yang berdiri di sana, cukup untuk kusandarkan saat lelah, cukup untuk kucari dukungan saat tersesat. Dulu, impulsivitasku bagaikan luka yang dalam pada harapan ayahku, luka tak terlihat namun lebih berat daripada teguran apa pun. Itulah tahun aku gagal ujian masuk universitas, guncangan pertama dalam hidupku membuatku depresi dan ingin menyerah. Malam itu, rumah terasa sunyi. Aku duduk meringkuk di kamar, menunggu celaan atau tatapan kecewa. Jantungku berdebar kencang seakan mau meledak.
Lalu pintu terbuka sedikit. Ayah masuk, tanpa suara. Aku mendongak, melihat mata Ayah dipenuhi kesedihan, tetapi tak ada air mata yang jatuh. Ayah tidak memarahi, tidak menghiburku dengan sia-sia, hanya duduk diam di sampingku. Ayah mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya dengan lembut di bahuku. Tangannya kasar, tetapi saat itu aku merasa seolah-olah menyalurkan sumber energi tak kasat mata kepadaku. Lalu Ayah berkata, suaranya hangat dan pelan: "Nak, satu pintu tertutup, tetapi banyak pintu lain akan terbuka. Yang penting adalah apakah kamu berani berdiri dan melangkah maju atau tidak." Aku membenamkan wajahku di telapak tanganku, air mata terus mengalir, membasahi bahu Ayah. Aku terisak, seolah ingin menyingkirkan semua kelemahan dan rasa rendah diri. Ayah tidak berkata apa-apa lagi, hanya meremas bahuku pelan, setiap tekanan teratur dan kuat, seolah memberi kekuatan pada anak yang sedang berjuang. Keesokan paginya, ketika aku bangun, Ayah sudah pergi bekerja. Di meja saya ada sebuah buku tentang orang-orang yang gagal tetapi pantang menyerah, dan selembar kertas kecil bertuliskan: "Ayah percaya kamu bisa. Bangun dan teruslah berjuang!". Saat itu, saya menyadari bahwa diamnya Ayah lebih berharga daripada seribu kata nasihat. Genggaman bahunya, tatapannya yang penuh tekad, dan selembar kertas kecil itu, semuanya adalah bukti kepercayaan tanpa syarat, sebuah dorongan yang tak perlu gembar-gembor.
Waktu mengalir tanpa henti, terus-menerus menguras tenaga seorang ayah, meninggalkan kerutan di wajahnya, dan membuat rambutnya semakin beruban dari hari ke hari. Namun, kasih sayang seorang ayah abadi, bagai bulan purnama yang menggantung di langit, menyinari jiwa setiap anak.
Sudah berapa lama sejak kau mengunjungi ayahmu, duduk di sampingnya mendengarkan kisah hidupnya? Tak pernah menggenggam tangannya, merasakan ketegaran dan kehangatan pengorbanan? Kembalilah, temani ayahmu—dan rasakan ketenangan paling damai di dunia, sebelum waktu menghapus cinta-cinta itu. Karena kita seringkali baru menyadari nilai sejati dari sebuah bahu, tatapan penuh kepercayaan, ketika segalanya telah menjadi kenangan. Dan saat itu, bahkan air mata asin pun tak mampu mengisi kekosongan...
Konten: Luong Dinh Khoa
Foto: Dokumen Internet
Grafik: Mai Huyen
Sumber: https://baothanhhoa.vn/e-magazine-lang-le-mot-bo-vai-259826.htm

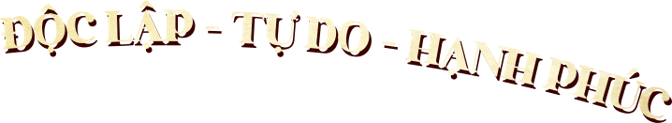

![[E-Magazine]: Diam-diam sebuah bahu](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/35d97dcb20a94a27a9c80af33ab8bb16)
![[E-Magazine]: Diam-diam sebuah bahu](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/9d6d37537e9c4a63b48634f899358a5a)
![[E-Magazine]: Diam-diam sebuah bahu](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/065ca67ca7b9455e86b2f308ff9d4aea)
![[E-Magazine]: Diam-diam sebuah bahu](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/a93091aad9ef489b8cd05f725f16a669)
![[E-Magazine]: Diam-diam sebuah bahu](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/e899ff1c2d25441fb51831a0bb935a8b)
![[E-Magazine]: Diam-diam sebuah bahu](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/88713e56dd584d43a5a62995e2170620)
![[E-Magazine]: Diam-diam sebuah bahu](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/48f520e170ef47e9a6d9f63994bc842d)
![[E-Magazine]: Diam-diam sebuah bahu](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/8cb8a329b47e4b9c886247912d43e6fb)
![[E-Magazine]: Diam-diam sebuah bahu](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/187b9c896e0c4c9d860bdf6039b4b262)



![[Foto] Warga antusias mengantre untuk menerima terbitan khusus dari Surat Kabar Nhan Dan](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/30/53437c4c70834dacab351b96e943ec5c)

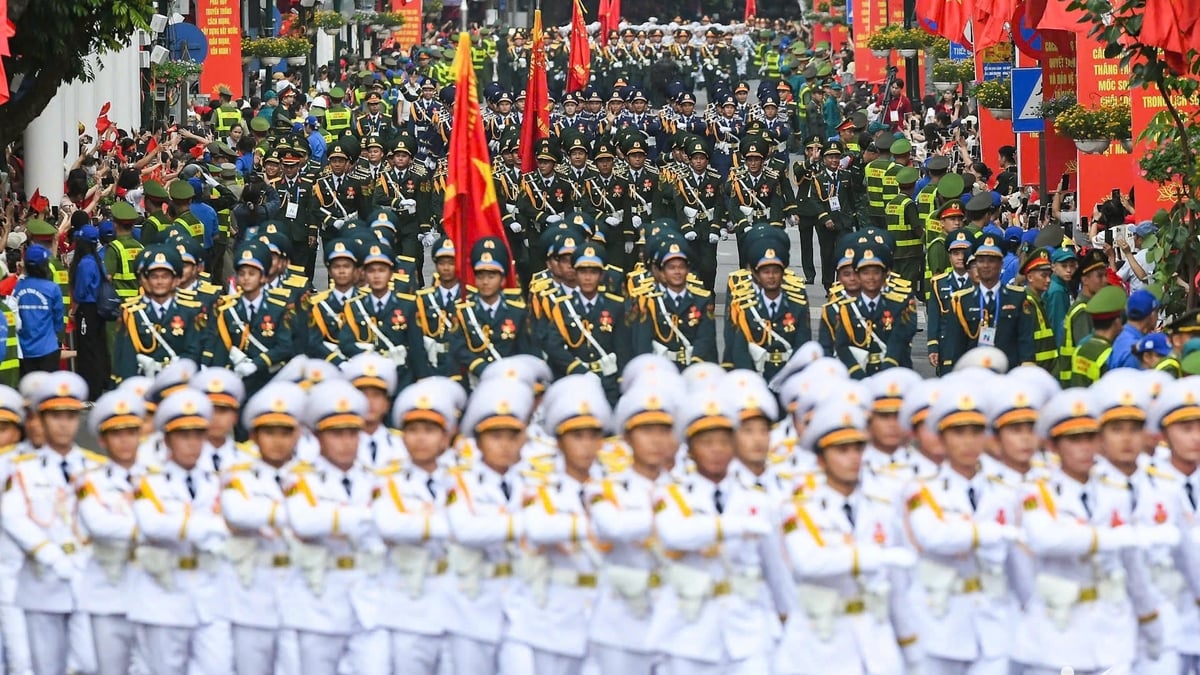






















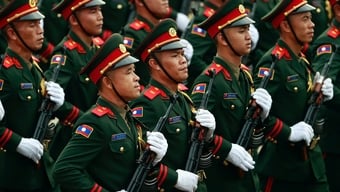










































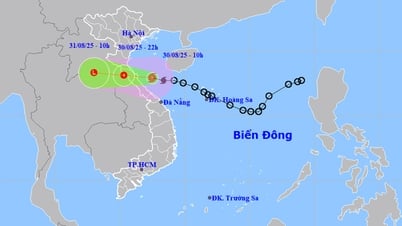































Komentar (0)